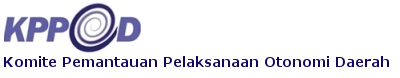Fenomena Lampung dan Imaji Otonomi Daerah 2045
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 -2045 yang sedang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas saat ini menjadi penentu nasib otonomi daerah di masa depan.
Betapa tidak, penyusunan rancangan ini terjadi di tengah fenomena Lampung—yang menjadi viral karena kedodoran dengan pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang rusak parah—dan suasana peringatan seperempat abad reformasi. Sebuah fenomena yang menggambarkan kinerja buruk daerah, termasuk sikap pemda yang antikritik, sekaligus intervensi pusat yang cepat mengambil alih urusan daerah.
Semesta tampaknya membunyikan alarm bahaya bagi keberlanjutan salah satu agenda reformasi tersebut, terutama jika ditempatkan pada ikhtiar mencapai Indonesia Maju 2045. Gejala ini bak mengamini dan/atau mengakomodasi pandangan negatif tentang otonomi daerah dan suara-suara resentralisasi yang menggema dalam ruang diskusi formal dan informal beberapa tahun terakhir.
Di sini, sebagian pihak membaca adanya ketidaksabaran pusat atas kinerja daerah. Yang paling serius, muncul pernyataan, ini adalah simtom kegagalan otonomi daerah.
Menyikapi arus balik desentralisasi
Gerakan arus balik desentralisasi ini mesti ditanggapi serius. Sebab, langkah ambil alih pusat merupakan ekspresi melempar batu sembunyi tangan.
Sesungguhnya, kerangka kebijakan dan desain hubungan pusat-daerah (kewenangan, fiskal, pembinaan-pengawasan) sendiri sebagai prakondisi bagi tumbuh-kembangnya otonomi daerah berada dalam situasi labil dan cenderung goyah mengikuti irama politis tertentu. Jika tak dibenahi secara sistematis, otonomi daerah pada 2045 berpotensi kehilangan signifikansi, alih-alih mendukung dan jadi rute efektif dalam mengakselerasi raihan misi Indonesia Maju.
Labilitas prakondisi
Prakondisi merupakan syarat perlu yang memungkinkan daerah otonom bekerja optimal. Evaluasi dua dekade otonomi daerah pascareformasi (KPPOD, 2020) mendiagnosis adanya ketidakstabilan prakondisi tersebut.
Prakondisi pertama adalah kebijakan tentang kewenangan daerah. Kewenangan mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat merupakan fondasi otonomi daerah. Mengadopsi pemikiran GL Clark (1984), kewenangan ini menjadi basis kebebasan dan kemandirian daerah berinisiasi (initiation) dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dan kebal (imunity) terhadap pengaruh dari otoritas lebih tinggi.
Namun, laku kebijakan pusat beberapa tahun terakhir bergerak erosif terhadap basis tersebut. Kecenderungan tersebut menubuh dalam sejumlah kebijakan strategis. Sebut saja Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang menarik kewenangan terkait perizinan sampai pengawasan dari daerah ke pusat. Selain berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah, beleid tersebut menghilangkan peran pengawasan pemda terhadap aktivitas pertambangan. Upaya ini tentu kontraproduktif dengan misi pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Pola serupa mewujud dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Dalam jagat soal yang diatur, UU ini menarik sejumlah kewenangan, antara lain terkait persetujuan pemanfaatan ruang (izin lokasi) jika daerah belum memiliki rencana detail tata ruang (RDTR), perubahan fungsi bangunan gedung, dan beberapa perizinan berusaha berbasis risiko, semisal urusan perindustrian dan perdagangan.
Penarikan ini mengancam keberlanjutan lingkungan lestari, inklusi sosial, ekonomi tangguh, dan tata kelola sebagai pilar daya saing daerah berkelanjutan.
Aroma resentralisasi juga tampak dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Kebijakan ini mengamanatkan pusat untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Meski mendukung kemudahan investasi dan pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing, langkah tersebut kontraproduktif dengan penguatan otonomi daerah.
Prakondisi lain adalah kebijakan tentang fiskal daerah. Kemandirian fiskal daerah menentukan derajat otonomi. Persoalannya, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih sangat tinggi. Data sebelum pandemi (BPK RI, 2019) menunjukkan ketergantungan daerah terhadap transfer pusat 80,10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kajian KPPOD (2020 dan 2022) menunjukkan kemandirian fiskal daerah jadi salah satu determinan rendahnya daya saing daerah.
Namun, narasi pusat tentang penguatan fiskal daerah tampaknya tidak tampak jelas dalam kebijakan terkait. Kajian KPPOD (2021) menunjukkan UU HKPD yang merevisi sekaligus UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah belum mampu membawa perubahan fundamental pada sisi pendapatan daerah. Kebijakan ini hanya menguntungkan kota dan kabupaten yang berkarakter urban dan unggul pada sektor jasa dan perdagangan. Alhasil, ketergantungan fiskal akan menjadi penyakit turunan daerah-daerah non-urban, terutama kabupaten-kabupaten yang jumlahnya jauh melampaui kota.
Harus diakui, pelaksanaan otonomi daerah selama dua dekade pascareformasi bukan tanpa masalah. Pada ruang administrasi, kita berhadapan dengan perubahan paradigma dan zig-zag transfer kewenangan yang begitu cepat.
Pada dimensi politik, partisipasi dan representasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan publik di daerah masih jauh panggang dari api. Kajian KPPOD (2017 dan 2019) tentang peraturan daerah (perda) bermasalah, misalnya, menunjukkan minimnya partisipasi publik dalam perancangan perda. Selain itu, persoalan korupsi pun turut mewarnai ragam permasalahan sebagai output dalam pelaksanaan demokrasi lokal.
Menurut data KPK, dalam kurun 2004 hingga Januari 2022, lembaga antirasuah tersebut telah menangkap 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota. Jumlah tersebut tentu bertambah mengingat setahun terakhir ada sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Sementara pada bidang ekonomi, selain masih labilnya prinsip pembagian urusan, sengkarut regulasi menimbulkan ketidakpastian. Pemda serba ragu dalam memfasilitasi kegiatan berusaha, sedangkan dunia usaha selalu wait and see untuk memulai dan terlibat dalam pembangunan ekonomi. Alhasil, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di daerah berjalan lamban.
Agenda pematangan
Kompleksitas masalah daerah tidak serta-merta diatasi dengan mengutak-atik kewenangan. Sebab, gestur zig-zag kebijakan ini merupakan pengingkaran eksistensial terhadap otonomi daerah. Konstitusi Republik Indonesia telah mengakui daerah sebagai ”korpus” Indonesia (Pasal 18 UUD 1945).
Rekognisi atas keberadaan daerah juga lahir dari kebutuhan sosiologis dan filosofis bangsa ini. Pusparagam konteks, karakter, dan kapasitas masyarakat serta kondisi endowment daerah yang berbeda-beda menuntut intervensi kebijakan dan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, dan pelayanan yang berbeda-beda.
Jika kita bertolak lebih dalam ke ruang filosofis, pengakuan terhadap identitas (kekhasan) dan adaptasi kebijakan terhadap konteks setempat merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.
Menggunakan kerangka pikir Dennis A Rondinelli dan Shabbir Cheema (1983), desentralisasi dan otonomi merupakan mekanisme yang akuntabel dalam menjalankan amanat konstitusi sekaligus peranti efektif dalam melakukan perencanaan, pengambilan kebijakan, penyusunan kelembagaan, dan memberikan pelayanan publik di tengah keberagaman daerah di Indonesia.
Justifikasi teoretis, konstitusional, dan sosio-filosofis ini menjadikan daerah sebagai elemen konstitutif dalam mencapai cita-cita maju pada usia emas Indonesia. Artinya, Indonesia Maju hanya akan tercapai jika, dan hanya jika, daerah juga berada pada derajat kemajuan atau berdaya saing tinggi, bahkan sangat tinggi. Itu adalah imaji otonomi daerah maju 2045. Otonomi daerah yang ditopang prakondisi yang matang.
Untuk mencapai kematangan tersebut, sejumlah agenda krusial perlu dilakukan. Pada level paradigmatik, pembagian kewenangan (urusan pemerintahan) harus teguh mengikuti prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemda. Prinsip ini menjadi parameter utama ketika UU sektoral mengatur sejumlah urusan yang menjadi kewenangan daerah sehingga tidak tumpang tindih dengan UU Pemda.
Lebih dari itu, berhadapan dengan capacity constraint dan tantangan karakter wilayah yang beragam, paradigma asimetri sudah selayaknya diperluas ke daerah-daerah lain dengan model yang bervariasi. Tentu harus selaras dengan karakter dan daya dukung tiap daerah.
Sementara pada level teknokratik, penguatan tata kelola yang baik. Tesis ”tidak ada daerah terbelakang, yang ada hanya daerah tak terkelola”, tidak sebatas kebenaran aksiomatis milik para ilmuwan dan pemikir kebijakan publik seperti Peter Drucker, tetapi sungguh-sungguh mengada dalam pengalaman empiris kita berdesentralisasi dan berotonomi pada era Reformasi.
Kajian-kajian KPPOD selama 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa otonomi daerah sebagai struktur kesempatan hanya bisa dikapitalisasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat jika, dan hanya jika, tata kelola yang baik sungguh-sungguh diwujudkan dan diutilisasi sebagai cara kerja dari peranti-peranti desentralisasi, mulai dari sistem kebijakan sampai desain hubungan pusat dan daerah yang partisipatif, akuntabel, dan transparan.
Penulis: Herman N Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD
Terbit pada Harian Kompas, 12 Juni 2024
Baca selengkapnya di sini: https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/12/fenomena-lampung-dan-imaji-otonomi-daerah-2045