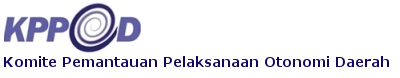Memikirkan Ulang Penataan Daerah
Sampai saat ini, Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tak kunjung terbit. Padahal, regulasi ini menjadi kompas penataan sehingga pemekaran, penggabungan, dan penyesuian daerah tidak bergerak liar mengikuti libido parokial tertentu.
Polemik pemekaran Papua beberapa waktu lalu pun semestinya menjadi titik pijak deliberasi baru untuk memosisikan penataan daerah sebagai program strategis nasional. Jika tidak, kisah sukses pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi angin segar bagi daerah lain untuk berakrobat membuka keran moratorium DOB.
Tak sebatas pemekaran
Penataan daerah merupakan peranti inheren dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama otonomi daerah. Undang-Undang Pemda menyatakan secara eksplisit bahwa penataan daerah merupakan jalan mempercepat pencapaian bonum commune, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, serta memelihara lokalitas (adat istiadat, budaya).
Dalam meraih tujuan tersebut, pemekaran bukan satu-satunya jalan. Masih ada penggabungan dan penyesuaian daerah (bdk Pasal 31 Pasal [3] UU Pemda). Namun, sepanjang penerapan otonomi daerah pascareformasi, pemekaran menjadi narasi tunggal nan mendominasi daripada penggabungan daerah. Padahal, penelitian Bappenas dan UNDP (2007) menunjukkan bahwa 80 persen DOB gagal. Dirjen Otda Kemendagri menyatakan dari evaluasi 57 daerah otonomi di bawah tiga tahun pada 2011-2012, misalnya, 67 persen bernilai kurang.
Menariknya, cerita-cerita gagal daerah hasil pemekaran tak menyurut usulan DOB. Meski terbit moratorium DOB sejak 2014, alih-alih berhenti, per Maret 2022, sebanyak 291 usulan DOB tercatat di Kemendagri, tak terhitung kampanye dan gerakan-gerakan menghimpun aspirasi masyarakat yang belum tercatat. Mengapa fenomena ini terjadi?
Pemekaran merupakan jalur pintas menuju dan/atau mendapatkan kekuasaan. Fenomena ini terbaca pada gestur aktor ”pejuang” pemekaran dan basis justifikasinya. Kelompok pertama, elite lokal dan diaspora dengan beragam profesi (pemuka masyarakat, politisi, pelaku usaha, birokrat, bahkan akademisi). Mereka menjadi pemeran protagonis yang aktif menyiapkan persyaratan, menggalakkan dukungan publik, dan mempengaruhi policy maker di pusat dan daerah.
Tesis mereka adalah pemekaran menjadi jalan bagi kesejahteraan masyarakat, efektivitas pelayanan, dan pemerataan pembangunan. Paling anyar, key words ini selalu dilontarkan pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan tiga RUU DOB Papua. Narasi ini sangat ampuh mengaduk-aduk emosi kelompok kedua, yaitu masyarakat akar rumput yang memang sangat mendambakan kesejahteraan dan pelayanan publik berkualitas.
Gerakan kelompok elite pun disambut sangat baik. Tak jarang, obrolan kelompok ini diwarnai glorifikasi potensi dan keberbedaannya dengan calon daerah induknya. Faktanya? Yang menikmati kue pemekaran adalah para politisi dan birokrat yang berpindah ke daerah baru tersebut. Sementara masyarakat tetap berada dalam ruang mimpi kesejahteraan.
Insoliditas desartada
Selain jalan pintas kekuasaan, meningkatnya usulan dan kontroversi DOB bersumber pada insoliditas desartada. Problem ini terbaca pada fakta, pertama, hingga saat ini, regulasi tersebut belum menjadi produk peraturan perundang-undangan.
Padahal, melalui desartada, publik memiliki basis informasi dan kerangka kerja valid terkait strategi penataan daerah dan estimasi jumlah pemekaran pada periode tertentu. Ketiadaan kebijakan ini berimplikasi pada fakta kedua, yaitu buruknya tata kelola (perencanaan dan monitoring-evaluasi) penataan daerah pascareformasi, terutama pada rezim UU No 23/2014.
Problem tata kelola tersebut tampak dalam sejumlah indikasi, antara lain ketiadaan evaluasi sistematis atas kinerja DOB. Beragam soal seperti daya saing rendah (KPPOD, 2020), kesenjangan antardaerah, dan ketidakpastian pelayanan publik menjadi bukti cukup untuk mengaktifkan klausul penggabungan dalam kebijakan penataan daerah.
Namun, cerita penggabungan tersebut tak pernah dan mungkin tak akan pernah terjadi di masa depan. Jangankan evaluasi atas DOB, evaluasi daerah persiapan (tiga tahun) tampaknya hanya sebatas formalitas sehingga selalu berujung kepada peningkatan status menjadi daerah baru.
Selain itu, polemik dan pembahasan pemekaran Papua menjadi contoh paling gamblang insoliditas desertada. Selain kebal dari kebijakan moratorium pemekaran, tiga DOB Papua juga tidak mengenal masa persiapan dan bahkan, Papua Selatan tidak memenuhi persyaratan dasar terkait cakupan wilayah minimal lima kabupaten/kota.
Padahal, masa persiapan menjadi tahapan krusial sekaligus menjadi kesempatan asesmen bagi peningkatan status menjadi daerah baru. Bahkan, untuk Papua, jika pemekaran tersebut ditempatkan dalam konteks kepentingan strategis nasional, durasi persiapan menjadi lima tahun (Pasal 49 Ayat 1 UU Pemda).
Akar persoalannya, UU Pemda tidak mengatur penataan untuk daerah yang dilabeli keistimewahaan atau kekhususan. Artinya, proses pemekaran, penggabungan, dan penyesuaian daerah seperti Papua atau DI Aceh diperlakukan sama dengan daerah lain.
Lebih dari itu, revisi UU Otsus menghapus ketentuan masa persiapan dalam proses pemekaran daerah di Papua. Pada titik ini, ketiadaan desartada membuka ruang tumpang tindih regulasi penataan daerah sekaligus membiarkan usulan-usulan pemekaran bergerak tanpa kepastian hukum.
Agenda ke depan
Memitigasi chaos lebih besar, penyusunan dan penetapan desartada mesti menjadi program prioritas nasional. Dalam rangka menghasilkan dokumen strategis tersebut, paradigma inklusivitas perancangan kebijakan harus menjadi pegangan bersama.
Ini menjadi prakondisi fundamental di tengah fenomena penyusunan regulasi ugal-ugalan yang marak terjadi akhir-akhir ini. Melalui paradigma ini, semua pemangku kepentingan, terutama dari daerah seperti pemda, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, memiliki akses yang sama, baik dalam proses kajian maupun penyusunan desartada.
Baca juga: Moratorium Pemekaran Wilayah dan Konsistensi Otonomi Papua
Mengikuti pemikiran pakar kebijakan publik William Dunn (2000), perancangan desartada hendaknya didesain seperti peramalan kebijakan (forecasting) di mana kelak publik bisa membaca dan diyakinkan tentang situasi lingkungan, sosial, dan ekonomi daerah pada masa mendatang. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai referensi strategi penataan dan jumlah ideal daerah, dokumen ini memberikan gambaran sejarah masa depan daerah, bahkan Indonesia.
Herman N Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) - Terbit di Kompas pada 28 Agustus 2022
Sumber: https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/28/memikirkan-ulang-penataan-daerah
Dibaca 916 kali