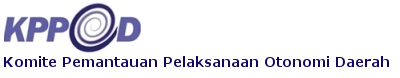Belajar dari Kisruh THR di Daerah
Nyaris tak pernah menjadi masalah serius pada tahun-tahun sebelumnya, pemberian tunjangan hari raya Lebaran 2018 bagi aparatur sipil negara memancing polemik publik. Secara keseluruhan negara mengalokasikan Rp 35,7 triliun untuk THR plus gaji ke-13 bagi pejabat/pegawai dan pensiunan. Angka ini naik 69 persen dibandingkan tahun lalu.
Polemik bermula dari protes sejumlah daerah. Mereka keberatan atas munculnya paket regulasi baru yang berimplikasi secara finansial, administrasi, dan bahkan hukum.
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018, PP No 19/2018 hingga Surat Edaran (SE) Mendagri No.903/3387/SJ pada Mei tak saja dinilai terlambat (mendadak), tetapi juga mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah (pemda) serta kerugian publik. Masalah payung hukum dan prosedur legislasi di daerah hingga ketidakpastian sumber anggaran dan besarnya tambahan alokasi belanja yang baru, mengemuka sebagai titik krusial perdebatan.
Substansi dan komunikasi
Terlepas dari sikap defensif Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sekurang-kurangnya dua poin berikut tetap perlu menjadi pembelajaran bagi pemerintah pusat dan pemda ke depan.
Catatan pertama menyangkut substansi kebijakan, khususnya perihal komponen tunjangan harj raya (THR). Bertahun-tahun THR aparatur sipil negara (ASN) itu berintikan gaji pokok (gaji bulan terakhir sebagai basis pengenaan) ditambah tunjangan melekat (jabatan dan keluarga).
Hal ini juga yang terkandung dalam UU No 15/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 (bagian dari perhitungan alokasi dasar dalam dana alokasi umum yang hampir mencapai Rp 195 triliun) maupun Peraturan Mentri Dalam Negeri No 33/2017 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Hingga disahkannya APBD 2018 di berbagai daerah pada kurun November-Desember 2017, skema dan formula THR seperti itulah yang diatur pemda dalam peraturan daerah (perda) APBD mereka.
Dengan demikian, semua daerah mestinya mengalokasikan THR. Jika sampai ada daerah lalai, kesalahan tentu terletak pada pemda bersangkutan, sekaligus menunjukkan lemahnya proses evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di pusat sehingga bisa meloloskan kesalahan ini. Hal ini, misalnya, terjadi pada Kota Surabaya, Kabupaten Rembang, dan Aceh Singkil. Jumlahnya tak banyak. Mayoritas daerah lainnya mengalokasikan THR dalam APBD, tetapi mereka tak memasukkan komponen baru yang dimunculkan dalam “paket regulasi Mei” tadi.
Pada titik ini, biang masalah adalah pemerintah pusat. Tunjangan kinerja (tukin) sebagai jenis komponen baru adalah susulan yang datang jauh setelah perda APBD disahkan, bahkan sudah setengah jalan dalam pelaksanaannya. Jika tukin ASN pusat bisa mulus saja diakomodasi lewat Peraturan Menteri Keuangan No 54/PMK.05/2018 yang terbit Mei 2018, tidak demikian halnya di daerah.
Sistem administrasi, prosedur birokrasi, dan payung hukum keuangan daerah tidak fleksibel dan adaptif terhadap perubahan mendadak pada pos kegiatan maupun mata anggarannya
Pusat tidak mengantisipasi dua kesulitan pihak daerah. Pertama, alokasi belanja suatu pos kegiatan baru jelas memerlukan penyesuaian dari sisi perencanaan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD Perubahan) hingga penganggaran (APBD Perubahan). Secara prosedural, keterlibatan DPRD jelas mutlak dalam pembahasan hingga persetujuan, meski Kemendagri menyatakan cukup melapor kepada pimpinan DPRD sesudah dilakukan perubahan dimaksud lantaran tambahan ini hanya berada pada level penjabaran APBD.
Alokasi tak berbasis perencanaan jelas malaadministrasi, bahkan potensial menjadi temuan dari instansi pemeriksa (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bisa berimplikasi serius dari sisi hukum.
Kedua, komponen baru itu tak saja berjumlah besar, tetapi juga menyulitkan pemda mengais-ngais sumbernya di pos belanja. Jika Kota Yogyakarta yang berskala kecil, pemda harus mencari tambahan untuk tukin sekitar Rp 33 miliar, bisa dibayangkan kabupaten/provinsi besar yang memiliki puluhan ribu ASN. Sementara ihwal sumber dana, opsi pergeseran anggaran, penjadwalan ulang kegiatan, atau penggunaan kas yang tersedia hanya boleh dilakukan saat situasi darurat (Pasal 28 Ayat 4 UU No 17/2003).
Jika efisiensi belanja birokrasi, seperti perjalanan dinas atau konsumsi rapat itu identik dengan mengurangi kenikmatan aparat dan belum tentu hasilnya menutupi jumlah besar yang dibutuhkan, maka jalan pintas di tempuh dengan cara memotong jumlah paket proyek (belanja modal, barang, dan jasa) sehingga unsur kerugian publik terjadi.
Selain perkara substansi, catatan kedua bagi pembelajaran ke depan adalah soal komunikasi kebijakan. Kasus ini kembali membuktikan tak kunjung beresnya relasi pusat-daerah di era otonomi. Ganjalan komunikasi menjadi ekspresi verbal dari (mis)manajemen pemerintahan, bahkan saat mengelola urusan diri mereka sendiri.
Pemerintah masih saja berlanggam sentralistik dalam mengelola desentralisasi. Ruang deliberasi untuk merundingkan perkara yang berimplikasi serius bagi daerah tidak difasilitasi, serta menutup opsi-opsi yang adaptif bagi daerah. Negosiasi keras justru terjadi di ruang publik: lewat media massa pusat dan sebagian daerah berbalas kritikan, berujung pada dibolehkannya daerah yang tak cukup kuat kapasitas fiskalnya untuk memakai skema lama.
Kemunculan paket regulasi Mei tersebut tidak lagi dibaca sebagai wujud perhatian negara guna menyokong aparaturnya bisa bersilaturahim dan mudik ke kampung halaman. THR juga kehilangan pesan formalnya sebagai instrumen insentif bagi ASN agar giat berunjuk kinerja, serta dibincangkan secara kurang bergairah terkait dampak gandanya bagi peningkatan daya beli dan kegiatan perekonomian.
Alih-alih, THR malah dicurigai sebagai gula-gula politik (politisasi THR) guna menarik dukungan ASN di tahun-tahun politik ini, sebagai cerminan dari watak politik anggaran yang acap lekat pada kepentingan politik rezim berkuasa (Irene S Rubin, “The Politics of Budgeting”, 2013).
Pekerjaan rumah
Momentum Lebaran memang telah lewat, tetapi perkara THR masih menyisakan pekerjaan rumah. Dalam jangka pendek adalah urgensi untuk meninjau ulang komponen THR Tampak janggal mengalokasikan THR sebesar take home pay, seperti tahun 2018 ini, apalagi masih ada gaji ke-13 yang masih harus dibayarkan hari-hari ke depan.
Melihat profil fiskal daerah di mana hanya 19 persen APBD dialokasikan bagi belanja modal (publik), kebijakan pusat ini memunculkan sentimen negatif masyarakat dan kontraproduktif secara politik.
Mengadopsi komponen tukin bukanlah praktik lazim, sulit dicari rujukan komparatifnya di negara lain atau sektor swasta. RAPBD yang disahkan jauh hari sebelum suatu tahun fiskal dijalankan pasti tidak bisa mengakomodasi insentif kinerja yang dinamis. Hal ini berbeda dari gaji dan tunjangan melekat (jabatan/keluarga): antara rencana dan realisasi hanya memunculkan pautan yang kecil dengan variabel kontrol yang bisa disimulasikan relatif persis sejak rancangan anggaran disusun.
Selanjutnya, dalam jangka panjang, agenda fundamental mereformasi penggajian ASN harus menjadi kebijakan politik nasional. Hingga lebih dari 70 tahun usia republik ini belum juga dibuat sistem remunerasi tunggal sehingga penjenjangan gaji berdasarkan hierarki jabatan maupun fasilitas/tunjangan berbasis kinerja tampak tak berpola.
Variasi antardaerah menimbulkan kecemburuan dan migrasi pegawai, serta membuka ruang gelap bagi praktik berburu rente dan korupsi (Indrayana, “Stop Penggajian Koruptif”, Kompas, 7/6/2018). Semua itu melibatkan dialog terbuka pusat dan daerah dengan sekuensi kebijakan yang bertahap, sistematis, dan bukan dadakan.
Penulis: Robert Endi Jaweng
Jabatan: Direktur Eksekutif KPPOD
Media: Harian KOMPAS – Selasa, 26 Juni 2018
--- o0o ---
Dibaca 1109 kali