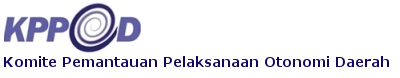Memperkuat Wakil Kepala Daerah
- 1 Januari 1970

Tapi, celakanya, respon yang kita berikan menyikapi bibit budaya unggul dalam organisasi tersebut seringkali justru primitif. Alih-alih mengkapitalisasi agar kian produktif kontribusinya, yang dilakukan malah mengebiri bahkan menyingkirkannya. Tragedi JK yang tidak dipasangkan kembali dalam duet bersama SBY dalam pilpres 2009 lalu adalah suatu pemisalan yang pas dari pemberian respon semacam ini. Cara-cara respon demikian ada pada level personal.
Namun, lebih mendasar lagi, bentuk respon dilakukan melalui rekayasa sistem, termasuk penggunaan instrumen regulasi. Hal ini, misalnya, yang sedang dicoba oleh DPD dan pihak-pihak lain untuk membedakan sistem pengisian jabatan antara kepala daerah dan wakilnya, bahkan menghilangkan posisi nomor dua tersebut dari struktur pemerintahan daerah. Sebagai suatu isu kebijakan yang mengemuka di parlemen, publik mesti beri perhatian dalam pembahasannya.
Apa Maunya?
Dalam hal Wakil Kepala Daerah, apa sesungguhnya yang kita mau dari posisi jabatan ini? Kalau Wakil Kepala Daerah dikritik lantaran hanya sebagai ban serep bahkan aksesoris dalam formasi kepemimpinan daerah, mengapa lalu yang justru diusulkan adalah pelemahan sumber lejitimasinya melalui perubahan sistem elektoral dari pemilihan langsung (rakyat) menjadi tak langsung/perwakilan (DPRD)? Mengapa pula dibedakan dari sistem elektoral yang berlaku pada Kepala Daerah yang niscaya tak saja menimbulkan kepincangan derajat dan otentisitas lejitimasi tetapi juga semakin mendistorsi kebermaknaan jabatan Wakil Kepala Daerah?
Ada pandangan, keberadaan Wakil Kepala Daerah tidak cukup berfaedah dan lebih sering memiliki hubungan bermasalah dengan Kepala Daerah. Saya pribadi tidak menyangsikannya, tapi sulit juga untuk percaya sepenuhnya. Dari cermatan lapangan selama 11 tahun mengunjungi ratusan daerah di seantero nusantara, pertanyaan itu memang terkonfirmasi di sejumlah kasus, namun lebih banyak sifatnya sebatas obrolan dan bahkan gosip yang tentu terlalu enteng untuk dijadikan input perubahan kebijakan. Berita media yang menyoroti sejumlah kasus (Bangkalan, Gersik, atau Riau, misalnya) mungkin memang mengesankan sesuatu yang gawat sedang terjadi, namun toh itu tetap hanya kasuistis.
Lebih jauh lagi, jika ada tendensi di periode berikutnya mereka pisah jalan, pecah kongsi, tak lalu berarti tanda adanya disharmoni saat pernah bersama dalam satu paket kepemimpinan, apalagi jika biang dituding kepada sang wakil semata. Terlalu banyak variabel yang menjelaskan fenomena pisah jalan, dari sekedar ambisi kekuasaan hingga kepercayaan diri bisa memimpin. Bagi sebagian Kepala Daerah, pilihan pisah jalan juga justru suatu kebanggaan tersendiri, bukti bahwa wakilnya bisa berkembang kapasitasnya setelah menjalani pengalaman berpemerintahan, sebagai tanda terbuka dan berjalannya proses kaderisasi pemerintahan itu sendiri.
Dengan pembacaan seperti itu, hemat saya, yang justru dilakukan adalah penguatan posisi dan kejelasan peran. Pertama, lejitimasi tetap berasal dari sumber yang sama (rakyat) melalui sistem elektoral yang tentu sama pula (pemilihan langsung). Tidak ada klaim berbeda sebagai produk murni (rakyat) dan produk perantara/wakil (DPRD), apalagi dalam hal lejitimasi politik tidak dibenarkan adanya perbedaan derajat dan otentisitas. Kalau lejitimasi adalah modal input, maka para pemimpin politik harus berasal dari hulu input yang sama.
Kedua, perbedaan baru dibuat pada fase proses berpemerintahan. Prinsipnya: otoritas keputusan hanya ada pada Kepala Daerah. Tak ada ceritanya Wakil bisa menandatangani produk hukum daerah (Perda, Perbup/Perwal, Kepbup/Kepwal). Sepenuhnya dan tidak bisa diwakili, otoritas itu hanya dipegang Kepala Daerah. Kalau demikian asasnya, kenapa kita cemas dengan konflik otoritas antara Kepala Daerah vs Wakil-nya? Tanpa tanda tangan Kepala Daerah maka tak akan ada instrumen kebijakan (regulasi dan fiskal) yang berlaku sah, seberapa dominannya pun pengaruh sang Wakil.
Di luar otoritas, ihwal proses manajerial pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik tentu membutuhkan pembagian kerja tertentu. Lantaran tingkatannya sudah soal manajemen, bukan lagi perkara lejitimasi dan otoritas, maka dasar pembagiannya adalah konsensus kedua pemimpin itu. Di sinilah masalah yang terkandung dalam konstruksi UU Pemda era otonomi: bukan semata pada tingkatan politik, tetapi bahkan ketika memasuki ranah manajemen kerja, Wakil tetap sama marjinal perannya. Wakil hanya menjadi pejabat “apabila (kondisional)”, yakni pengganti saat Kepala Daerah tak berada di tempat/berhalangan dan berperan seremonial.
Pada titik perbaikan di level manajerial ini, kita patut “belajar” pada sistem Orde Baru yang memang mumpuni mendesain manajemen kerja. Wakil Kepala Daerah terasa hadir sosok dan kinerjanya lewat lini sektoral dan kewilayahan, serta efektif dalam mengkoordinasi pengelolaan daerah. Kalau Sekda membantu Kepala Daerah pada tugas pembinaan sumber daya aparatur dan penataan birokrasi, Wakil mengambil peran substantif dalam manajemen pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik. Semua ini soal kerja, bukan politik.
Jadi, alih-alih membonsai apalagi menghapuskan eksistensi Wakil Kepala Daerah, yang kita butuhkan adalah penguatan lebih subtantif pada matra manajemen berpemerintahan. Intinya di situ adalah kejelasan pembagian kerja, yang tentu bisa dirumuskan sebagai konsensus (kontrak kerja) antar Kepala Daerah dan wakilnya saat maju dalam ajang pilkada. Hal ini pasti sulit untuk dirundingkan jika keduanya tidak maju dalam satu paket yang sama atau dihasilkan dari sistem elektoral berbeda.
Oleh Robert Endi Jaweng
Manajer Hubungan Eksternal KPPOD, Jakarta
--- (Dimuat di Tabloid KONTAN - Sabtu, 03 September 2011) ---
Dibaca 871 kali