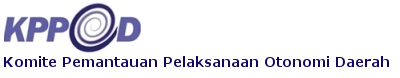Memperkuat Desentralisasi Pertambangan?
- 1 Januari 1970

Uji materill ini diajukan Bupati Kutai Timur, Isran Noor, terhadap Presiden RI (Menteri ESDM) yang menilai lemahnya kewenangan Kabupaten/Kota dalam tata kelola pertambangan, sekaligus gugatan atas kewenangan yang justru lebih besar di level Propinsi dan Pusat atas sumber daya ekstraktif tersebut. Dengan keputusan itu, Mahkamah Konstitusi hendak memindahkan otoritas dari Pusat ke Pemda perihal penetapan wilayah pertambangan (WP), wilayah usaha pertambangan (WUP), luas dan batas wilayah ijin usaha pertambangan.
Namun, atas penetapan wilayah oleh Pemda tersebut, Pusat berhak memberikan penolakan apabila dinilai tidak sejalan dengan rencana tata ruang maupun tumpang tindih dengan ijin-ijin pertambangan yang sudah diberikan sebelumnya di dalam area yang sama. Hak penolakan Pusat ini memang berbentuk rekomendasi, namun tingkat daya ikatnya bersifat otoritatif karena menentukan berlanjut atau sebaliknya dibatalkan usulan penetapan yang disampaikan Pemda.
Kalau kita cermat membaca klausul keputusan di atas, secara substansi sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pengelolaan Minerba ke depan. Otoritas penetapan WP dan WUP masih tetap dipegang Pusat. Perbedaan hanya terjadi pada proses: kalau sebelumnya Pusat menetapakan wilayah peruntukan dan kemudian dikoordinasikan dengan Pemda, sekarang Pemda yang pertama-tama menentukan wilayah dan diusulkan kepada pusat untuk ditetapkan.
Selain itu, keputusan MK tersebut lebih menegaskan “decentralization flavour” dalam konteks pembuatan kebijakan publik (pertambangan). Meski Pusat tetap memegang otoritas akhir, namun proses pengajuan kebijakan berasal dari daerah. Dengan keputusan itu, koordinasi antar tingkat pemerintahan juga menjadi lebih tegas karena Pusat tidak bisa membuat keputusan tanpa melibatkan daerah dan/atau adanya usulan dari pihak daerah.
Jadi, hemat saya, keputusan MK atas Pasal 6 (1) UU No.4/2009 hanya merubah alur proses: dari top-down (wilayah pertambangan ditetapkan Pusat setelah berkoordinasi dengan Pemda) menjadi bottom-up (Pusat menetapkan wilayah pertambangan berdasarkan usulan dan penetapan terlebih dulu oleh Pemda).
Dalam konteks kewenangan atas pertambangan, seperti pula berbagai sektor strategis lain seperti kehutanan dan perikanan, model sentralisasi dan desentralisasi selalu menjadi perdebatan selama ini. Bahkan hingga kini, Pemerintah masih belum mantap betul letak level otoritas yang tepat dalam hal kewenangan pengaturan dan/atau pengurusan atas sektor-sektor tersebut. Upaya terbaru Pemerintah adalah lewat revisi UU No.32/2004 tentang Pemda yang saat ini sedang dibahas di Panja DPR di mana urusan pertambangan, kehutanan dan perikanan diusulkan untuk diatur Propinsi, sementara Kabupaten/Kota hanya memperoleh bagi hasil fiskal (skema DBH SDA terkait).
Di masa Orde Baru, sentralisasi tata kelola pertambangan menjadi pilihan kebijakan yang nyaris tanpa reserve. Dalam rezim sentralisasi (UU No.1/1967 dan PP No.32/1969), pusat memegang kuasa atas galian golongan A dan B, Propinsi kebagian golongan C, sementara Kabupaten/kota tidak mendapat tempat. Pemerintah seolah memanfaatkan celah Konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) yang menggariskan kepemilikan --- kepenguasaan Negara (Pusat?) atas bumi, air dan kekayaan di dalamnya --- suatu basis argumentasi yang coba dihidupkan lagi dalam kerangka revisi UU Pemda saat ini.
Namun, sejak awal penerapan otonomi, pergeseran kekuasan pengelolaan mulai mengarah ke aras lokal. UU No.22/1999 dan penggantinya UU No.32/2004 mengatur secara umum bahwa kewenangan atas urusan pertambangan tidak lagi dimonopoli Pusat. Penguatan pada level kebijakan makro ini kemudian dijabarkan dan diperkuat pada aturan sektoral berupa UU No.4/2009, meskipun Pemda tidak selalu merasa puas sebagaimana ditunjukkan oleh upaya judicial review di atas.
Arah dasar legislasi baru (baik makro maupun sektoral) tersebut adalah hendak menjaga titik imbang antara prinsip kepentingan nasional, kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, dan desentralisasi pengelolaan,
Pertama, kebijakan baru ini meletakkan fondasi bagi penguatan hak kuasa Negara atas SDA, yang dilaksanakan Pemerintah lewat otoritas mengatur dan mengawas pengelolaan usaha tambang. Untuk itu, UU Minerba memulai dengan perubahan rezim kontrak menjadi rezim perijinan. Di sini terjadi reposisi Negara sebagai pemegang kuasa dan tidak lagi di sejajarkan dengan kontraktor yang selama 42 tahun membuat posisinya sering berdaya tawar lemah di depan pemodal besar pertambangan.
Kedua, wilayah pertambangan (WP) menjadi dasar pemberian ijin. Pusat menetapkan WP, dan semua perijinan di daerah wajib disesuaikan dengan perwilayahan tersebut. Pemda diharapkan akan lebih terukur dalam memberi ijin. Perwilayahan tersebut juga disinkronkan dengan tata ruang nasional agar menjamin kepastian berusaha tanpa dihantui lagi dengan perubahan fungsi lahan menjadi kawasan konservasi, taman nasional, hutan lindung, dll.
Ketiga, arsitektur perijinan lebih sederhana. Sebelumnya ada 6 jenis KP, kini menjadi 2 perijinan: eksplorasi dan operasi produksi. Para pelaku usaha, domestik maupun asing, juga berkesempatan sama dalam memproses perijinan karena adanya mekanisme lelang terbuka wilayah usaha. Yang patut diselesaikan di level PP nanti adalah ihwal jangka waktu dan batas luasan lahan yang kurang selaras dengan kebutuhan lazim industri pertambangan.
Melihat sejumlah point perubahan di atas, UU No.4/2009 sesungguhnya lebih memberi arah jelas bagi desentralisasi pertambangan dibandingkan UU No.11/1967 yang digantikannya. Di bawah UU Minerba yang baru, ruang daerah terbuka lebar dan garis pembagian kewenangan menjadi lebih jelas. Pusat hanya punya kewenangan eksklusif atas: (a) kebijakan nasional, (b) pembuatan peraturan, (c) penetapan standard/pedoman (d) sistem perijinan nasional, serta (e) penetapan WP. Di luar itu, kewenangan (perijinan) pusat-daerah bersubstansi sama dan hanya berbeda dalam skala wilayah: kabupaten/kota dalam yurisdiksinya dan wilayah laut sampai 4 mil, propinsi untuk lintas kabupaten/kota dan wilayah laut 4-12 mil, Pusat untuk lintas propinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
Tugas yang mesti dijamin berhasil kemudian adalah: substansi perubahan dalam UU Minerba yang baru tadi memang bisa dibuktikan pada tingkat implementasi. Koordinasi horizontal lintas sektor dan pelibatan pihak Pemda harus mulai ditunjukan saat penyusunan sejumlah RPP saat ini. Lalu, terkait tantangan desentralisasi pertambangan tadi, Pemda harus lebih giat membangun kapasitas kerja agar siap menjalankan fungsi mengatur perijinan dan pengawasannya di lapangan.
Problem Implementasi
Menurut saya, isu implementasi saat ini jauh lebih penting ketimbang merubah kebijakan, termasuk melalui upaya hukum judicial-review yang mungkin saja akan muncul lagi. Pada tingkat implementasi, daerah tidak bisa sembarangan menetapkan ribuan jenis ijin di mana satu-sama lain tumpang-tindah, tidak mengindahkan kaidah good mining practices. Dari hasil rekonsiliasi sementara atas data-data izin usaha pertambangan saat ini, Pusat mengidentifikasi bahwa dari total jumlah izin usaha pertambangan yang saat ini mencapai 10.566 izin terdapat sekitar 5.940 yang masih non-clean and clear (3.988 izin operasi dan produksi mineral, serta 1.952 IUP operasi dan produksi batubara) sehingga daerah maupun perusahaan terkait dilarang mengekspor hasil tambang yang ada.
Sementara pada level pusat, isu implementasi terkait keharusan Pemerintah untuk segera membuat peta WP dan WUP sebagai dasar bagi daerah untuk menerbitkan ijin. Dengan keputusan MK, proses dibalik: daerah yang sekarang dituntut untuk segera menentukan WP dan WUP tersebut, dan Pusat harus segera merespon dengan upaya verifikasi dan pemberian persetujuan/penolakan atas hal tersebut.
Lebih dari isu letak kewenangan (policy problem), yang harus menjadi fokus ke depan adalah konsistensi menerapakan regulasi (UU dan berbagai aturan turunannya), membangun kapasitas pelaksanaan yang kuat di berbagai level otoritas, dan koordinasi yang efektif antara Pusat dan daerah (implementation problem).
Kalau tidak, seberapa banyak pun upaya judicial review yang hendak dilakukan, kita akan tetap menghadapi aneka problem klasik pertambangan: bad-mining practices, rebutan kewenangan Pusat-Daerah, tumpang-tindih perijinan atau pun ijin-ijin liar, dll.
Oleh Robert Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD, Jakarta
--- (Dimuat di Bisnis Indonesia – Kamis, 29 November 2012 – Hal.Opini) ---
Dibaca 1156 kali